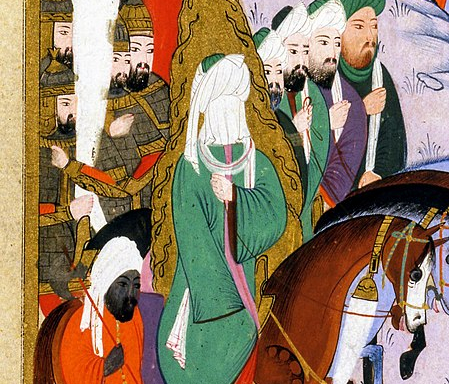Dengan diturunkannya manusia ke tempat rendah itu (Asfala Safilin), manusia menjadi memiliki kesempurnaan forma.

Oleh Haidar Bagir
Sambil membaca tafsir Ibnu Arabi tentang laylatul qadar beberapa waktu lalu, saya menyempatkan diri memahami ulang tafsir Sang Syaikh soal ayat: “(Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk) lalu kami tolak mereka ke tempat yang paling rendah (Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh….),” (at-Tin: 4-5).
Menurut Ibnu Arabi, ada tiga kemungkinan tafsir atas ayat tersebut. Yang pertama dan kedua hanya disinggung secara sekilas oleh Ibnu Arabi. Pada dasarnya kedua makna ini sejalan dengan makna populer yang dipahami orang. Yakni bahwa (sebagian) manusia – yang sebetulnya memiliki potensi kebaikan/kemuliaan – justru mengikuti hawa nafsu rendahnya sehingga cenderung melakukan amal-amal keburukan. Maka mereka pun tak mendapat apa-apa karena hanya berkutat di kerendahan maqam ruhani.
Nah, kemungkinan, pemahaman ketigalah yang menarik. Yakni pemahaman yang berkonotasi positif terhadap keterturunan manusia ke tempat rendah itu. Bahwa, justru dengan diturunkannya manusia ke tempat rendah itu, manusia jadi memiliki kesempurnaan forma (bentuk). Asfala safiilin (dalam surat at-Tin: 5) di sini dipahami sebagai materi (maddah) dari alam syahadah/thabi’i (alam fisik) sebagai hadhrah ilahiyah yang terendah dalam tajalliy-Nya.
Kenyataan bahwa manusia ditempatkan di alam materi ini menjadikannya mungkin untuk mendaki tangga keberadaannya menuju potensi “sebaik-baik bentuk” (ahsan taqwim, dalam surat at-Tin: 4) itu. Yakni ruh Ilahiah – disebut al-ruh al-mudabbirah – yang memungkinkannya mengembangkan sifat-sifat Ilahiah. Sifat-sifat Ilahiah ini biasa disebut sebagai fadhl (keanggunan) yang lebih bersifat ruhani dan adl (ketegasan/keadilan) yang lebih rasional: sifat-sifat lembut dan keras secara sekaligus.
Sedemikian, sehingga dalam tafsirnya itu Ibnu Arabi menyebut bahwa manusia menjadi cermin-Nya Allah. Maka, sengaja saya tidak sebut kedua kelompok sifat itu sifat-sifat kebaikan dan keburukan. Karena, sesungguhnya, sebagaimana sifat lembut bisa menjadi keburukan jika tak dikombinasikan dengan ketegasan, maka sifat keras bisa menghasilkan kebaikan jika ditempatkan di tempat yang benar.
Kesempurnaan ini, kata Ibnu Arabi, merupakan imitasi dari kesempurnaan (kamal) Allah yang terbentuk dari kepemilikan dua kelompok sifat-Nya, yakni fadhl dan adl, atau jamal dan jalal, secara seimbang. Bukankah manusia memang diciptakan atas fitrah-Nya (ar-Rum: 30) dan, di dalam hadis, “manusia diciptakan dlm citra-Nya”? Meski, sebagaimana halnya dengan sifat-sifat Allah Swt, keseimbangan itu terbentuk dalam dominasi sifat jamal atas jalal-Nya, fadhl atas adl.
Kiranya ini sejalan dengan pemahaman Aristoteles tentang etika sebagai pencapaian the golden mean. Yakni bersikap moderat dalam segala hal, sebagai hasil racikan yang pas antara sifat lembut dan keras. Orang yang dermawan saja, tanpa disiplin finansial, akan menjadi pemboros; Pemberani yang kehilangan rasa takut, akan menjadi sembrono; Orang baik yang tidak punya rasa marah, akan lembek; dan seterusnya.
Maka, kita pun pada akhirnya diingatkan oleh Ibnu Arabi juga, bahwa bertasawuf – belajar dari hadis Nabi saw – tak lain adalah mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan kita secara seimbang dengan meniru keseimbangan sifat-sifat Ilahi. At-takhalluq bi Akhlaq Allah (Berperilaku seperti perilaku Allah)….
Pada akhirnya, sebagaimana diungkapkan dalam ayat setelahnya (at-Tin: 6), (tak ada yang bisa mencapai keseimbangan itu sehingga bisa mendaki tangga menuju ruh keilahian) kecuali orang-orang yang beriman (kepada Tuhan dan adanya maqam ruhaniah tertinggi yang bisa dicapai manusia) dan beramal saleh (sesuai dengan fitrahnya).
Di sisi lain, juga pernah saya baca/simpulkan dari suatu bagian dari Futuhat, bahwa penurunan manusia ke alam fisik ini memberinya akses kepada tanda-tanda (ayat Allah) di alam fisik. Suatu akses yang malaikat dan jin tidak memilikinya. Malaikat yang bersifat ruhani hanya bisa mendapatkan akses kepada alam ruhani – dalam makna mengetahui secara sudah jadi – tanpa melewati pelajaran yang bisa diambil lewat perenungan memdalam atas tanda-tanda di alam fisik dan khayali.
Sementara, jin tak punya akses ke alam fisik, selain akses ke alam khayali dan – bisa juga – ke alam ruhani. Padahal akses ke alam fisik ini bisa menjadi sumber keimanan dan kedalaman ilmu tentang hakikat segala sesuatu. Demikianlah, dikatakan oleh Alquran, ulul albab memiliki kedalaman marifat dan pengetahuan sebagai hasil mengamati dan merefleksikan beragam obyek fisik dan sosial di dalamnya, termasuk fenomena alam, seperti pergantian malam dan siang serta penciptaan langit dan bumi (Q.S. Ali Imran 3:190-191), siklus kehidupan tumbuhan yang tumbuh karena air hujan dan akhirnya mati (Q.S. Az-Zumar 39: 21), fenomena sosial seperti sejarah atau kisah masa lampau (Q.S. Yusuf 12:111), dan sebagainya.
Catatan Akhir:
Sebagian orang keberatan dengan cara Ibnu Arabi menafsirkan ayat-ayat ini. Adanya potongan “‘illa’ (kecuali) orang-orang yang beriman dan beramal saleh,” bermakna bahwa “asfala safiliin” adalah tempat yang buruk, yakni tempat orang-orang yang tak beriman dan tak beramal saleh.
Hal ini menurut penulis sangat mudah dijelaskan. Pertama, melihat susunan/bentuk kalimat ayat, dan ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa Allah ingin mengungkapkan suatu keniscayaan bahwa manusia ditakdirkan dicipta dalam sebaik bentuk dan juga niscaya diturunkan ke asfala safilin. Semua manusia. Ya, penurunan itu adalah bagian dari takdir/fate-nya manusia. Jadi, semua manusia diturunkan.
Maka, jika demikian, kata illa pasti tak merujuk pada makna adanya orang yang tak diturunkan ke asfala safilin. Dia merujuk ke sesuatu yang lain. Yakni, seperti diuraikan di atas, ada orang yang tetap berada di asfala safilin, ada yang bisa mendaki ke puncak bentuk terbaiknya itu. Ayat itu pun menjadi bermakna, bahwa orang akan tetap berada secara status quo di asfala safilin, kecuali jika dia beriman dan beramal saleh. Wallahualam