Kaidah yang disebut dengan basith al-haqiqah kullu asyya’ ini dipakai oleh para filosof Muslim, khususnya dalam mazhab filsafat Hikmah, untuk menegaskan kemanunggalan dan kesederhanaan eksistensi yang abstrak. Makin abstrak suatu hakikat makin sederhana dan makin utuh semua sifat kesempurnannya.
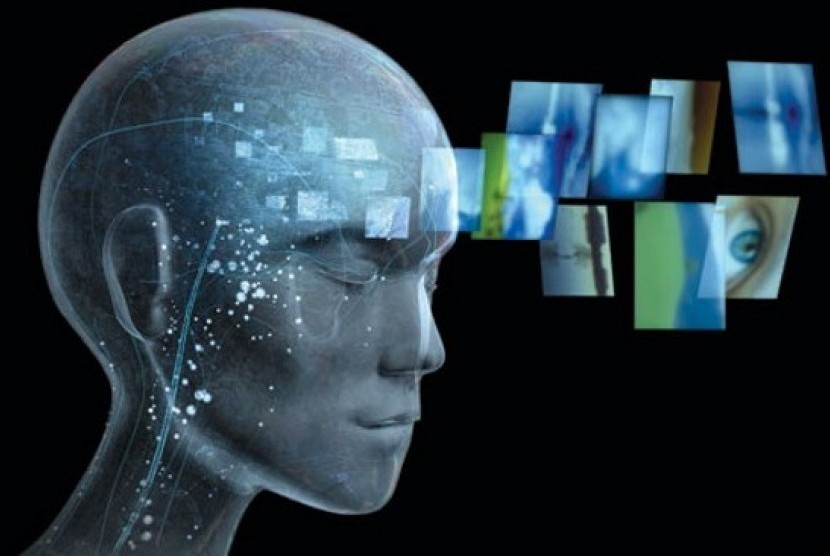
Kaidah Pertama
Untuk menjawab kontroversi akal dan kalbu, ada baiknya kita pahami kaidah filosofis yang dapat meluruskan salah satu sumber kerancuan berpikir yang lazim terjadi dalam wacana-wacana abstrak dan filosofis. Yakni kecenderungan orang untuk meletakkan pembahasan filosofis dan mistis dalam kerangka fenomena material dan jasmani.
Padahal, perwujudan abstrak seperti kategori-kategori kesempurnaan, keberakalan, dan pengetahuan bersifat sederhana dan manunggal. Perbedaan dan pembedaan hanya dipakai untuk tujuan menjelaskan, menguraikan, dan mengandaikan sesuatu.[1]
Modus eksistensi abstrak senantiasa bersifat manunggal, sederhana dan universal, yang berbeda dengan sifat benda-benda material yang majemuk dan terbagi-bagi ke dalam satuan-satuan khusus yang terbatas.
Oleh karena itu, di dalam tataran eksistensi abstrak, tidak ada kebodohan versus akal. Yang ada sebenarnya hanyalah akal versus tingkat-tingkat akal di bawahnya.
Tingkat-tingkat kekurangan akal itu lalu dipersepsi dan diungkapkan sebagai kebodohan, yang bersifat relatif terhadap kesempurnaan akal mutlak. Demikian pula halnya dengan kesempurnaan versus kekurangan, kebaikan versus kejahatan, kebenaran versus kebatilan, dan sebagainya.[2]
Upaya membedakan akal dengan kebodohan untuk tujuan-tujuan analitis dan argumentatif sering merancukan dan menyesatkan pikiran dalam menelaah wacana-wacana di alam abstrak.
Kaidah yang disebut dengan basith al-haqiqah kullu asyya’ ini dipakai oleh para filosof Muslim, khususnya dalam mazhab filsafat Hikmah, untuk menegaskan kemanunggalan dan kesederhanaan eksistensi yang abstrak. Makin abstrak suatu hakikat makin sederhana dan makin utuh semua sifat kesempurnannya.
Berdasarkan kaidah tersebut, para filosof menyimpulkan bahwa sifat-sifat Allah identik dengan Zat-Nya yang dinyatakan dengan rumusan shifatul-llah ‘aynu dzatih. Sifat Allah identik dengan Zat-nya dan bersumber dari dalam Zat Yang Mahasuci lagi Mahatinggi itu sendiri.[3]
Kaidah yang sama juga dapat diterapkan pada hakikat atau sifat yang abstrak seperti akal, pengetahuan, pengalaman, kesadaran, kesempurnaan dan kemaujudan. Hakikat-hakikat dan sifat-sifat abstrak itu tidak bisa dibeda-bedakan, semuanya bersumber pada kemaujudan atau kesempurnaan yang sama.
Kebergandan atau bahkan keberagaman yang tampak di alam material tidaklah nyata dan hakiki, melainkan relatif atau nisbi, aksidental atau tambahan, kiasan atau andaian (putative). Yang hakiki dan nyata ialah kemaujudan, akal, pengetahuan, dan kebenaran, sementara lawannya bersifat relatif dan mengikut (bin nisbah ila atau bil idhafah ila) pada keberadaan yang sempurna.[4]
Ada dua contoh keberadaan andaian dan relatif;
Pertama, keberadaan warna dalam cahaya. Menurut fisika, foton-foton atau partikel-partikel terkecil cahaya yang memancar dari suatu sumber memiliki energi yang berbeda-beda. Indra kita menangkap beragam denyar energi itu sebagai warna, yang sama sekali tidak bisa dibilang ada vis-a-vis cahaya. Sebaliknya, cahaya adalah satu-satunya yang secara objektif ada, sedangkan warna hanya ada sebagai kiasan dan pantulan cahaya dalam persepsi indra manusia.
Kedua, keberadaan nol dalam matematika. Secara bahasa, nol didefenisikan sebagai the complete absence of quantity (ketiadaan kuantitas). Meskipun hampa dan tidak punya kuantitas, nol adalah andaian yang bisa efektif bila diberi angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tanpa diberi angka di depannya, berapa pun banyaknya, deretan nol takkan berhasil-guna. Secara filosofis, ia disebut sebagai tiada (non-being) atau relatif (nisby).
Dengan demikian, dalam menelaah eksistensi abstrak seperti akal, pengetahuan, kebenaran, kesempurnaan, kekuasaan dan sebagainya orang tidak boleh gegabah. Watak kesederhanaan dan kemanunggalan kategori-kategori tersebut harus senantiasa dipelihara.
Dalam bahasa filsafat, kesederhanaan (basathah atau simplicity) bermakna keadaan asli dan hakiki sesuatu yang senantiasa menyertainya. Karena itu, keliru bila kita menganggap sifat kesalahan atau kebatilan dapat secara mandiri (independent) melawan sifat kebenaran, sehingga seolah ada dua sifat yang sedang bertempur dalam posisi yang seimbang dan setara.[5]Sebab, yang sebenarnya terjadi ialah berkurangnya cahaya kebenaran at the expense of menguatnya kegelapan kebatilan secara relatif.[6] (MK)
Bersambung…
Sebelumnya:
Catatan kaki
[1] Penjelasan menarik seputar masalah ini dapat dilihat pada Murtadha muthahari dan S.M.H. Thabathaba’i, Menapak Jalan Spiritual, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hal. 66.
[2] Tentang makna pembedaan dan perbedaan, lihat Murtdha Muthahhari, Keadilan Ilahi, Bandung: Mizan, 1992, hal. 98-99.
[3] Murtadha Muthahhari, Neraca Kebenaran dan Kebatilan, Bogor: Cahaya, 2001. Lihat juga Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi, Op Cit.
[4] Mulla Shadra, Mafatih al-Ghayb, Mu’assasa-e Muthala’at va Tahqiqat Farhang, 1363 Tahun Iran, pada pengantar Muhammad Khajawi.
[5] Ghulam Heusein Ibrahim Deydani, Qawa’id-e Kully Falsaf-e Islam, Mu’assasa-e Muthala’at va Tahqiqat Farhang, 1419 H, dengan merujuk pada kata basith.
[6] Istilah ‘kerajaan’ ini mengacu kepada hadis Nabi yang sangat masyhur. Lihat Sachiko Murata, The Tao of Islam, Bandung: Mizan 1996, hal. 317-318.

