Tradisi kelimuan kaum Alawiyin (Habaib) dikenal juga dengan “Thariqah Alawiyah”. Meski tak bisa lepas dari dasar-dasar teoretis pemikiran kesufian, Thariqah Alawiyah bukanlah suatu orde sufi (tarekat). Ajaran ini, lebih menganjurkan pada berbagai praktik mujahadah dan riyadhah untuk mengembangkan keadaan-keadaan spiritual tertentu yang melahirkan akhlak yang baik. Oleh sebab itu, Thariqah Alawiyah dikelompokkan ke dalam apa yang biasa disebut sebagai “tasawuf akhlaki”.
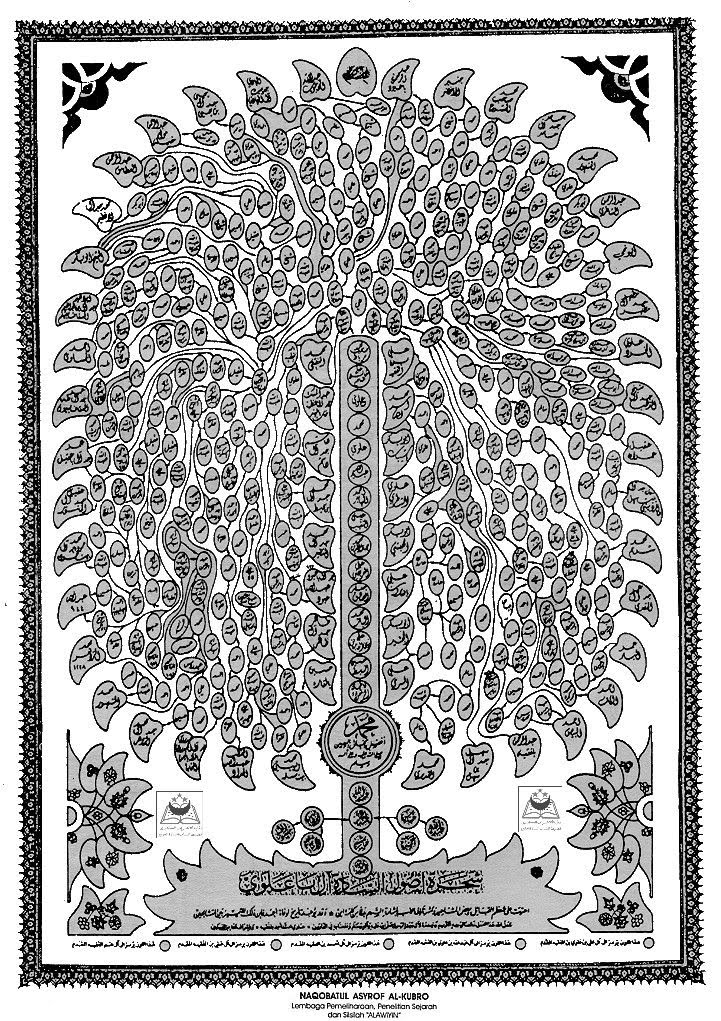
Thariqah Alawiyah yang didirikan oleh Al-Faqih Al-Muqaddam, pada masa selanjutnya menjadi semacam “mazhab” atau jalan hidup kaum Alawiyin di mana pun mereka berada. Meski bukan suatu bentuk orde sufi (tarekat) pada umumnya, tapi secara umum kita bisa menilai bahwa sistem ajaran ini sangat kental nuansa tasawufnya.
Musa Kazhim, menkualifikasikan Thariqah Alawiyah ini sebagai suatu bentuk cara beragama yang berorientasi tasawuf. Namun, tak seperti thariqah pada umumnya, Thariqah Alawiyah bukanlah suatu orde sufi (tarekat), meski tak bisa lepas dari dasar-dasar teoretis pemikiran kesufian, Thariqah Alawiyah bisa dikelompokkan ke dalam apa yang biasa disebut sebagai “tasawuf akhlaki”. Dengan kata lain, ketimbang mempromosikan pemikiran-pemikiran teoretis dan spekulatif—yang biasanya hanya dibatasi pada sekelompok elite ulamanya (khawwash) di kalangan mereka—thariqah ini lebih menganjurkan pada berbagai praktik mujahadah dan riyadhah untuk mengembangkan keadaan-keadaan spiritual tertentu yang melahirkan akhlak yang baik. [1]
Untuk mengenal lebih jauh terekat ini, berikut ini beberapa prinsip Thariqah Alawiyah sebagaimana dikutip dari buku “Peran Dakwah Damai Habaib/Alawiyin di Nusantara”:[2]
Sayidina Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, dalam kumpulan ucapannya yang terdapat dalam An-Nahr Al-Maurud, mengatakan, “Sesungguhnya, thariqah Alawiyah lahiriahnya adalah ilmu-ilmu agama dan amal, sedangkan batiniahnya adalah mewujudkan maqamat dan ahwal, adabnya adalah menjaga rahasia dan cemburu terhadap penyalahgunaannya. Jadi, lahiriahnya adalah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, berupa ilmu dan beramal menurut cara yang benar, sedangkan batiniahnya adalah, seperti yang diterangkan oleh Asy-Syadzili, berupa mewujudkan hakikat dan memurnikan tauhid. Ilmu mereka adalah ilmu orang-orang besar. Ciri khas mereka adalah menghilangkan bentuk simbol.”[3]
Mereka memohon kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada-Nya dengan segala pendekatan. Mereka melakukan pengikatan janji, talqin (menuntun bacaan zikir), dan pemakaian khirqah (kopiah atau jubah untuk penahbisan ke thariqah), riyadhah (olah rohani), mujahadah (pengorbanan dalam menundukkan nafsu), serta mengikat persahabatan. Mujahadah mereka yang terbesar adalah berjuang untuk menyucikan hati dan menyiapkan diri untuk menerima anugerah-anugerah kedekatan (dengan Allah) pada jalan kebenaran. Mendekatkan diri kepada Allah dengan segala pendekatan dalam persahabatan dengan orang-orang yang mendapat petunjuk. [4]
Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah ditanya tentang pengertian thariqah Alawiyah. Beliau mengatakan, “Lahiriahnya adalah Ghazaliyyah dan batiniahnya adalah Syadziliyyah. Artinya, lahiriahnya adalah mengosongkan (melepaskan) diri dari akhlak tercela dan menghiasi diri dengan akhlak terpuji, sedangkan batiniahnya adalah penyaksian akan anugerah Allah dari sejak awal langkahnya.” Beliau mengatakan, “Jika mau, Anda dapat mengatakan, ‘Thariqah Alawiyah adalah keselamatan dan istikamah, pertemuan dan penghadapan, pengosongan dan penghiasan diri, petunjuk dan ketenangan, penghapusan dan penetapan, usaha yang keras dan penanggungan beban, atau keselamatan dan penyerahan’.”
Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqih, bahwa thariqah tersebut mengikuti nash menurut cara khusus. Kemudian, beliau mengatakan bahwa jalan para salaf adalah beramal di tempat dia harus beramal, meninggalkan tempat yang harus ditinggalkan, berniat di tempat dia harus berniat, dan mengungkapkan di tempat dia harus mengungkapkan. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, “Thariqah Ahlulbait adalah amal. Mereka tidak menuntut ilmu, kecuali yang menuntun kepada amal dan untuk menjaga diri mereka, sedangkan yang lainnya mereka terima dari limpahan anugerah Allah. Mereka mengambil ilmu, baik yang muthlaq (tidak terbatas oleh individu dan lingkungan) maupun muqayyad (yang terbatas oleh individu dan lingkungan) dari keberadaan takwa.”
As-Sayid Al-Allamah Ahmad bin Abubakar bin Sumaith, semoga Allah memberi manfaat melaluinya, berkata, “Sesungguhnya, thariqah Alawiyah telah mencakup rahasia-rahasia yang tidak didapati pada thariqah Islam lainnya dan thariqah ini berbeda dengan sifat-sifatnya yang tinggi. Sebab, dalam hal hakikat pemurnian dan pengesaan, dibangun di atas jalan Asy-Syadziliyyah dan mereka yang berjalan sesuai dengan jalan itu, sedangkan mujahadah dibangun di atas jalan Al-Ghazali. Thariqah ini tidak disisipi penyimpangan apa pun, bahkan mereka yang berada dalam thariqah ini melanjutkan yang ada di sepanjang zaman, saling mewarisi generasi demi generasi, hingga di zaman kita saat ini.[5]
Hubungan dengan Ibn Arabi
Dalam analisis yang lebih jauh, thariqah Alawiyah sebenarnya memiliki hubungan yang erat dengan konsep Panteisme (tauhid wujud) Ibn Arabi.
Haidar Bagir, seorang penggagas Gerakan Islam Cinta, dalam salah satu tulisannya pernah mengemukakan bahwa ada kemungkinan besar penerimaan Islam yang luas di masyarakat Nusantara disebabkan adanya kesesuaian antara panteistik Islam yang dibawa oleh para Wali Songo dan ulama-ulama sesudahnya dengan teologi Hinduisme (Vedantic, bukan populer) yang telah tertanam dalam budaya pemikiran bangsa Nusantara sebelumnya. Lebih lanjut menurut Haidar Bagir, pada kenyataannya, dalam penelitian yang lebih serius, bukan hanya Syaikh Siti Jenar, tapi para anggota Wali Songo keseluruhan adalah para guru panteisme.[6]
Dalam kesempatan berbeda, Haidar Bagir pernah pengutarakan bahwa paham panteisme tersebut masuk ke Nusantara dengan dibawa oleh kaum Alawiyin dari Hadramaut. Dalam artikel berjudul “Napas Cinta dari Hadramawt” yang pernah dipublikasi oleh Majalah Tempo tahun 2012, Haidar Bagir mengungkapkan bahwa thariqah Alawiyah secara prinsipil mengacu pada konsep sufistik Ibn Arabi. [7]
Dalam artikel tersebut Haidar Bagir mengisahkan bahwa Al-Syaikh Abu Madyan Syuaib bin Abu Hasan At-Tilmisaniy Al-Maghriby (guru Ibn Arabi), yang pada saat itu sedang berada di Tilmisan, Al-Jazair, mengutus muridnya yang bernama As-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Al-Maqad, seraya bertitah:
“Sesungguhnya kami mempunyai seorang sahib di Hadramaut (Tarim), pergilah engkau menemuinya, dan pakaikanlah khirqa ini kepadanya. Sesungguhnya aku melihatmu akan menemui ajal di tengah perjalanan. Bilamana hal tersebut akan terjadi, maka titipkanlah jubah ini kepada orang yang engkau percayai.”
Kemudian pergilah Al-Syaikh Abdurrahman dari Tilmisan ke Hadramaut. Ketika sampai di Kota Mekah, dia pun disergap sakratulmaut. Maka, kemudian diserahkannya jubah tadi kepada muridnya, yaitu Al-Syaikh Abdullah Al-Salih al-Maghriby seraya berpesan agar menyampaikannya kepada yang berhak. Hingga Syaikh Abdullah sampai ke Tarim dan menyerah-terimakannya kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, sebagaimana yang diamanahkan Abu Madyan.
Menurut catatan, pemberian khirqa dari Syaikh Abu Madyan kepada Al-Faqih Al-Muqaddam merupakan awal tenggelamnya beliau dalam suluk (pelancongan spiritual), mujahadah (upaya keras menundukkan nafsu rendah) dan riyadah (latihan-latihan spiritual) yang menjadi tonggak-tonggak tasawuf.
Meski demikian, sebagaimana kita lihat pada sejumlah prinsip thariqah Alawiyah sebelumnya, tidak disebutkan sama sekali tentang Ibn Arabi. Tapi menurut Haidar Bagir, “Sebab, dalam lingkungan tarekat ini, ajaran Ibn Arabi dibatasi aksesnya hanya pada kaum elite spiritual (khawash) saja. Bagaimanapun, sebagai sebuah ajaran tasawuf, prinsip cinta dan metode dakwah damai menjadi ciri utama tarekat ini.”[8]
Dengan prinsip-prinsip inilah mereka menyebarkan Islam di Nusantara, sehingga mudah diterima dan dihayati oleh masyarakat setempat. Pada masa selanjutnya, ajaran ini menjadi corak kebudayaan Islam di Nusantara. Hingga tiba satu masa, ketika Imperium Majapahit runtuh, dan kolonialisme bangsa Eropa dimulai, corak kebudayaan ini pun berubah. Ajaran Islam yang sebelumnya dihayati secara laten, muncul kepermukaan, dan bertransformasi ke dalam bentuk identitas politik. (AL)
Bersambung…
Sebelumnya:
Catatan kaki:
[1] Lihat, Musa Kazhim, “Sekapur Sirih Sejarah ‘Alawiyin dan Perannya Dalam Dakwah Damai Di Nusantara: Sebuah Kompilasi Bahan”, dalam Peran Dakwah Damai Habaib/’Alawiyin di Nusantara, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013), hal. 6
[2] Peran Dakwah Damai Habaib/’Alawiyin di Nusantara, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013)
[3] Ibid, hal. 7
[4] Ibid. hal. 8
[5] Ibid, hal. 9
[6] Lihat, Haidar Bagir, Islam dan Budaya Lokal, dalam ‘Islam Nusantara; Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan”, Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (Edt), Bandung, Mizan, 2016, hal. 178
[7] Lihat, Haidar Bagir, “Napas Cinda dari Hadramaut”, Majalah Tempo, Minggu 12 Agustus 2012
[8] Lihat juga, https://islamindonesia.id/kolom/opini-nafas-cinta-dari-hadhramawt.htm

