Di tengah gemerlap kehidupan jahiliyah yang menyelimuti kota Mekkah, keluarga Abu Thalib menjadi sekelompok orang yang berbeda sendiri. Ketika orang-orang mengumpulkan harta dengan cara berjudi dan memainkan riba, keluarga ini justru terus melestarikan tradisi kedermawanan Hasyim dan Abdul Muthalib.
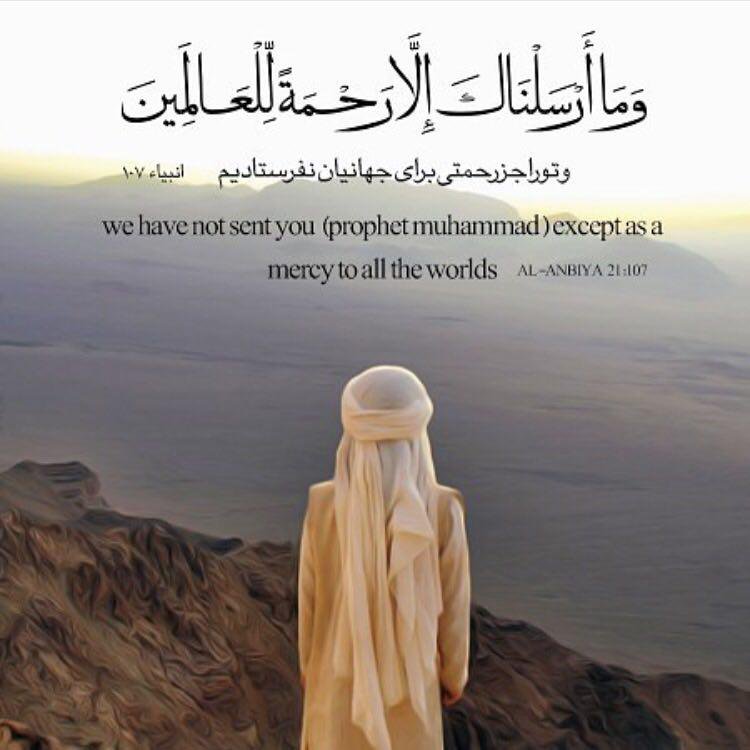
@MuhammadMovie
Sebagaimana sudah sedikit kita ulas pada edisi sebelumnya, bahwa di tahun yang sama dengan waktu Abrahah menyerang Kabah, lahirlah cucu Abdul Muthalib yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ketika itu Muhammad lahir dalam keadaan yatim, karena ayahnya wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan. Abdullah sendiri adalah putra ke sepuluh Abdul Muthalib dari istrinya yang bernama Fatimah binti Amr. Dari Fatimah ini, Abdul Muthalib dikaruniai 8 orang anak, diantaranya; Abu Thalib; Zubair; Arwah; Atiqah; Ummu Hakim; Barrah; Umaimah; dan Abdullah.[1]
Tapi meskipun terlahir sebagai yatim, Muhammad tidak kekurangan kasih sayang. Dia begitu dicintai oleh ibu, kakek dan paman-pamannya. Pribadi Muhammad demikian memukau dan akhlaqnya begitu mulia. Penduduk Makkah demikian membanggakannya, bahkan kelak mereka memberikannya julukan Al-Amin, yang artinya sangat terpercaya.
Tapi di usianya yang masih 6 tahun, Muhammad kehilangan ibunya, dan dua tahun setelah itu – atau pada pada usia ke delapan – dia pun kehilangan kakeknya. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, tampuk kepemimpinan Bani Hasyim diambil alih oleh putranya yang bernama Abu Thalib.
Salah satu Riwayat mengisahkan, bahwa ketika menjelang wafatnya, Abdul Muthalib sempat memanggil dan mengumpulkan semua putranya. Pada kesempatan itu Abdul Muthalib mengatakan, bahwa dia meninggalkan dua warisan; pertama, adalah tampuk kepemimpinan Bani Hasyim; dan kedua, adalah Muhammad bin Abdullah, yaitu keponakan mereka yang masih berusia delapan tahun.
Kemudian Abdul Muthalib bertanya, siapa yang menginginkan kekuasaan dan siapa yang menginginkan hak asuh atas Muhammad bin Abdullah? Kebanyakan dari mereka memilih kekuasaan dan menolak untuk merawat Muhammad bin Abdullah. Kecuali satu, Abu Thalib.
Kakak kandung Abdullah ini maju ke hadapan ayahnya dengan penuh keyakinan, bahwa dia hanya menginginkan hak asuh atas Muhammad bin Abdullah, dan sama sekali tidak tertarik dengan tampuk kekuasaan Bani Hasyim.
Tapi melihat ketuluasan putranya ini, Abdul Muthalib akhirnya memutuskan Abu Thalib mendapat keduanya; yaitu sebagai pemimpin klan Bani Hasyim, dan juga sebagai memegang hak asuh atas Muhammad bin Abdullah.
Abdul Muthalib pun mengumumkan hal ini kepada semua orang menjelang wafatnya, dan dia meminta semua putranya serta semua orang dalam klan Bani Hasyim untuk berbaiat kepada Abu Thalib sebagai pemimpin klan selanjutnya. [2]
Maka demikianlah, sejarah meratifikasi bahwa Abu Thalib menjadi pemimpin Bani Hasyim setelah Abdul Muthalib, sekaligus pemegang hak asuh Muhammad bin Abdullah. Kedua legitimasi ini melekat pada dirinya secara tak terbantahkan. Dia menjalankan kepemimpinan Bani Hasyim secara bijak, sehingga Bani Hasyim menjadi salah satu klan yang paling disegani di kalangan suku Quraisy dan bangsa Arab.
Di sisi lain, sebagaimana sejarah membuktikan, kecintaan Abu Thalib pada kemenakannya memang sangat dalam. Bahkan Abu Thalib dan istrinya yang bernama Fatimah binti Asad lebih mendahulukan kepentingan Muhammad ketimbang putra-putrinya sendiri.
Hanya saja, setelah era kepemimpinan Abdul Muthalib, situasi yang dihadapi Abu Thalib bukan semakin mudah, malah semakin rumit dan kompleks. Karena yang sekarang dihadapinya adalah sebuah konstruksi sosial masyarakat yang jauh lebih kosmopolitan, lebih mapan dan lebih dinamis dari sebelumnya. Pada era ini, Kaum Quraisy sedang menapaki era keemasannya, dan Kota Makkah kini benar-benar memenuhi takdirnya “Ummul Qura”.
Di tengah gemerlap kehidupan jahiliyah yang menyelimuti kota Mekkah, keluarga Abu Thalib menjadi sekelompok orang yang berbeda sendiri. Ketika orang-orang mengumpulkan harta dengan cara berjudi dan memainkan riba, keluarga ini justru terus melestarikan tradisi kedermawanan Hasyim dan Abdul Muthalib.
Hasilnya, sudah bisa diduga. Harta keluarga Abu Thalib secara berangsur menyusut.
Di dalam dinamika kehidupan jahiliyah, materi adalah panglima. Abu Thalib pun harus merelakan sejumlah tanggungjawab yang diembannya di kota Mekkah untuk diberikan kepada anggota klan lain yang lebih mampu. Tugas sebagai pemberi makan peziarah (Rifadah),[3] segera berpindah pada keluarga Umayyah yang ketika itu sangat berkuasa karena kekuatan materinya.[4]
Tak ayal, meski tinggal di tengah-tengah keluarga yang terhormat dan mulia, masa kanak-kanak Muhammad tak lepas dari kerja keras. Dia seringkali pergi ke gurun untuk menggembala binatang ternak pamannya. Di sinilah, menurut para sejarawan, Muhammad kecil banyak merenungi situasi zamannya.
Di sinilah dia melihat kesengsaraan dan kebobrokan agama, pemandangan yang tak akan pernah hilang dari pikirannya. Dengan rendah hati dan tanpa menonjol, dengan beragam pikiran memenuhi benaknya, Muhammad yang suka menyendiri itu pun tumbuh dari anak-anak menjadi pemuda, dan dari pemuda menjadi dewasa. (AL)
Bersambung…
Sebelumnya:
Catatan kaki:
[1] Lihat, Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, (Yogyakarta: Navila, 2008), hal. 9
[2] Lihat, Sayyid Ali-Asghar Razwy, Restatement History Islam and Muslims, https://www.al-islam.org/restatement-history-islam-and-muslims-sayyid-ali-asghar-razwy, diakses 22 Juni 2022
[3] Tinjauan lebih jauh mengenai jabatan-jabatan di Kota Mekkah dakwah Rasulullah Saw, bisa merujuk pada serial Abdul Muthalib yang pernah dipublish ganaislamika.com. lihat, https://ganaislamika.com/abdul-muthalib-1-rantai-nasab-yang-mulia/
[4] Lihat, Syed Ameer Ali, Op Cit, Hal. 12-13

