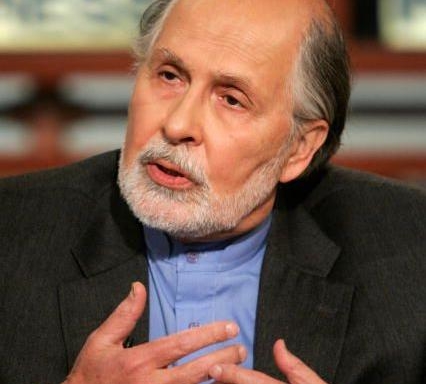Pengilmuan Islam bertujuan untuk mengkontekskan teks-teks agama; dengan kata lain, menghubungkan agama dengan kenyataan.

Oleh Zainal Abidin Bagir[1]
Islamisasi Ilmu versus Pengilmuan Islam (1)
Di atas “pengilmuan Islam” dicoba dipahami dengan membandingkannya dengan Islam sebagai mitos dan ideologi. Untuk lebih jauh memahami ini dalam konteks yang lebih luas, kita bisa melihat alternatif lain bagi gerakan “pengilmuan Islam”. Dalam konteks yang berbeda, Kunto membandingkan pengilmuan Islam dengan kodifikasi Islam dan islamisasi ilmu (ISI, 6-11).[2] Pengilmuan Islam (yang dalam konteks ini disebutnya sebagai demistifikasi Islam) adalah gerakan dari teks ke konteks; islamisasi adalah sebaliknya, dari konteks ke teks; sementara kodifikasi berkutat di sekitar eksplorasi teks, nyaris tanpa memperhatikan konteks. Ketiga gerakan ini adalah ragam perwujudan dari keinginan untuk kembali kepada teks (Alquran dan Sunnah).
Dalam beberapa pembahasan Kunto, pengilmuan Islam terkadang sulit dibedakan dari islamisasi ilmu, dan tampaknya di tulisan-tulisan awalnya Kunto tak secara ketat membedakan keduanya. Atau, penjelasan yang menurut saya lebih memuaskan adalah bahwa Kunto sesungguhnya telah mengubah posisinya mengenai gagasan islamisasi ilmu, yang di tahun 80-an dan 90-an merupakan gagasan yang amat populer di dunia Muslim. Perubahan posisi Kuntowijoyo tampak cukup jelas dalam buku Islam sebagai Ilmu yang mengandung bab-bab yang ditulis pada 1991 hingga 2004.
Sebagai contoh, di bukunya Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991) dia menyebutkan secara positif (dan eksplisit) upaya islamisasi ilmu yang dipahami sebagai upaya perumusan teori yang didasarkan pada paradigma Alquran (ISI, 26). Dia juga tak bersepakat dengan Ziauddin Sardar yang mengkritik upaya Islamisasi ilmu pengetahuan (ISI, 93). Namun dalam tulisannya yang terbit pada tahun 2002, dia menghadapkan pengilmuan Islam sebagai alternatif bagi islamisasi ilmu (ISI, 6). Di pengantar buku itu, Kunto bahkan secara tegas mengatakan, “… gerakan intelektual Islam harus melangkah ke arah ‘pengilmuan Islam’. Kita harus meninggalkan ‘Islamisasi pengetahuan’….” (ISI, 1).
Di tulisan-tulisannya yang belakangan itu, tampak setidaknya ada dua pembedaan pengislaman ilmu dengan pengilmuan Islam. Perbedaan pertama adalah dalam hal metodologinya. Yang pertama tampaknya lebih bersikap reaktif, yaitu reaksi terhadap bangunan keilmuan yang sudah wujud, yang dipandang tak sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan ingin dikembalikan kepada Islam yang lebih dipahami sebagai teks (ISI, 8). Pengilmuan Islam memiliki sikap yang lebih terbuka dalam hal ini. Gerakan ini dengan rendah hati mengakui bahwa penggagasnya lahir di alam ilmu-ilmu sekular, yang terkadang tampak bermusuhan dengan agama.
Sementara umat beriman mungkin memiliki keberatan terhadap sebagian bangunan ilmu kontemporer, namun mereka tak ingin menggantikan ilmu-ilmu sekular (ISI, 53). Berangkat dari keyakinan akan misi profetik agama (transendensi, emansipasi dan humanisasi), yang diinginkannya adalah memastikan bahwa agama dapat memainkan peran yang cukup besar dalam memastikan keberlangsungan hidup dan masa depan umat manusia. Salah satu kritik gerakan ini terhadap ilmu-ilmu sekular adalah bahwa yang belakangan sedang terjangkiti krisis, dalam artian tak dapat memecahkan persoalan (ISI, 52).
Di sinilah terletak perbedaan kedua dengan islamisasi ilmu. Pengilmuan Islam sesungguhnya bukan hanya persoalan keilmuan saja; salah satu tujuan utamanya adalah mengkontekskan teks-teks agama; dengan kata lain, menghubungkan agama dengan kenyataan. Istilah lain yang bisa digunakan di sini adalah “membumikan Islam”. Kenyataan hidup adalah konteks bagi keberagamaan. Ketika berbicara tentang ilmu sosial profetik, dia bahkan lebih jauh menyebut bahwa ilmu sosial ini bersifat transformatif.
Jadi, di satu sisi, yang diinginkan adalah justru melanjutkan perjalanan ilmu-ilmu sekular, dan mencoba memperbaiki dari dalam. Pencapaian ilmu-ilmu sekular tak dinafikan, tapi diintegrasikan dalam suatu kerangka teoretis baru yang punya keberpihakan cukup jelas kepada nilai-nilai humanisasi/emansipasi, liberasi, dan transendensi (ISI, 52, 57). Kerangka teoretis inilah yang ingin diturunkan Kuntowijoyo dari kitab suci (dalam hal ini, Alquran).
Secara umum, bagi Kunto, modal utama untuk memperbaiki ilmu-ilmu modern adalah agama. Agama penting dilibatkan di sini justru karena keberpihakannya cukup jelas, yaitu kepada kepentingan kemanusiaan (yang, sebagaimana disinggung di atas, dijabarkan menjadi humanisasi, liberasi, dan transendensi) . Namun, sekali lagi, ini mensyaratkan bahwa agama lebih dulu diobjektifikasi, agar benar-benar bermanfaat untuk seluruh umat manusia, tak hanya absah bagi pemeluknya.
Bersambung ke:
Sebelumnya:
Catatan
Kaki:
[1] Zainal Abidin Bagir, Ph.D, saat ini beliau merupakan Direktur Program Pasca Sarjana Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gajah Mada. Tulisan ini pernah disampaikan beliau dalam diksusi tentang pemikiran Kuntowijoyo yang diadakan Masyarakat Yogyakarta untuk Ilmu dan Agama (MYIA) dan Badan Koordinasi Mahasiswa Sejarah (BKMS) UGM, 26 Mei 2005, di UGM. Atas izin penulis, Redaksi Gana Islamika diperkenankan untuk menerbitkannya.
[2] ISI: Islam Sebagai Ilmu, Jakarta: Teraju-Mizan, Juni 2004.