Pada masanya, Abu Hanifah dianggap sebagai sosok yang kontroversial karena metode rasionalnya dalam menetapkan hukum Islam. Oleh ulama tradisional, dia dianggap sebagai ancaman bagi validitas hukum dari tradisi kenabian.
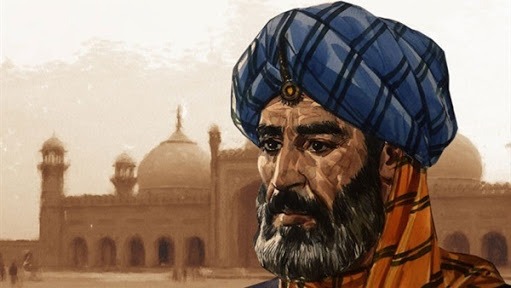
Numan bin Tsabit bin Zuta (80–150 H/699–767 M), atau lebih dikenal sebagai Abu Hanifah, atau sebagai “Imam Besar” (al-Imam al-Azam), adalah salah satu tokoh intelektual terpenting Islam pada masa awal-awal. Melalui dirinya, dasar-dasar metodologi hukum rasional dalam Islam berhasil diletakkan, dan dengan demikian, dia membuka jalan atas munculnya konseptualisasi prinsip-prinsip hukum universal normatif melalui metode rasional dan pertimbangan utilitas sosial dan manfaat.[1]
Abu Hanifah juga melakukan pembelaan terhadap metode-metode yang dilakukan oleh kaum rasionalis untuk menyimpulkan kasus hukum. Secara umum, kaum rasionalis adalah orang yang memperoleh pengetahuan dengan cara berpijak kepada informasi-informasi primer (data awal), dan lalu dengan informasi-informasi primer ini, mereka membangun pengetahuan baru.[2]
Di kemudian hari, Abu Hanifah dikenal sebagai peletak dasar-dasar mazhab Hanafi, salah satu mazhab fikih terbesar dan tertua di dalam dunia Islam. Meskipun di Indonesia mayoritas penduduknya penganut mazhab Syafii, namun di belahan dunia lain, mazhab Hanafi menjadi mazhab yang dominan, misalnya di Yordania, Lebanon, Pakistan, Suriah, Turki, Uni Emirat Arab, Bangladesh, Mesir, India, dan Irak. Konstitusi Afghanistan juga banyak merujuk kepada fatwa-fatwa Mazhab Hanafi.
Selain itu, pada abad ke-16, Kekhalifahan Turki Usmani diketahui telah mengadopsi mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara. Turki Usmani meresmikan kitab Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah, yang mana telah disusun untuk menyamakan rujukan hukum para hakim di bawah kekhalifahan Turki Usmani yang sebelumnya tidak memiliki kitab kompilasi hukum yang menjadi rujukan bersama. Kitab hukum ini diadopsi dari kitab-kitab muktabar dalam mazhab Hanafi.[3]
Sekarang mari kita kembali ke pembahasan tentang metode rasionalis yang dianut oleh Abu Hanifah. Dalam kasus ilmu hukum, kaum rasionalis, sebagaimana telah dijelaskan di atas, melalui rasionalisasinya atas sumber hukum awal, maka mereka akan menghasilkan hukum baru yang mereka harapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam kehidupan sosial.
Dengan metode rasionalis seperti itu, oleh karenanya, pada masa itu Abu Hanifah dianggap sebagai sosok kontroversial yang secara pemikiran bertentangan dengan para ahli hukum Islam kontemporer yang memegang teguh yurisprudensi berbasis hadis (ahl al-hadith).
Para ahli hukum yang berorientasi tradisional memandang metode-metode Abu Hanifah, yang berdasarkan pada penalaran independen (ijtihad), terutama yang berkaitan dengan penalaran analogis (qiyas) dan preferensi hukum (istihsan), sebagai ancaman terhadap validitas hukum dari tradisi kenabian.[4]
Selain itu, pandangan-pandangan teologis Abu Hanifah juga menjadi kontroversi tersendiri, membuat para kritikusnya menyebut dia sebagai seorang Murjiah, meskipun dia sendiri menolak pelabelan ini.[5] Ada banyak definisi terkait sekte Murjiah ini, sehingga cukup sulit untuk menentukan mana yang sebenarnya. Yang membuatnya menjadi cukup rumit adalah karena di balik lahirnya sekte ini, ada nuansa teologis dan politik yang mewarnainya, yakni terkait posisi kekhalifahan yang sah di antara Khulafaur Rasyidin.[6]
Namun, untuk memudahkan pembahasan, kita akan mengambil salah satu definisi Murjiah dari al-Syahrastani (lahir 479 H), salah seorang ulama tafsir dan fikih. Menurut al-Syahrastani, kata Murjiah berakar pada kata irja, kata benda abstrak atau verbal noun, yang memiliki dua arti. Pertama, irja berarti “menunda,” dan “menempatkan pada urutan berikutnya.” Kedua, irja juga bisa diartikan “memberi harapan.”
Untuk arti pertama, bisa digunakan ketika penganut Murjiah menunda suatu tindakan (amal) setelah adanya niat atau persetujuan dan kesediaan (untuk menjalankan doktrin agama). Untuk arti kedua dapat diterapkan ketika penganut Murjiah menyatakan “jika orang sudah beriman perbuatan dosa tidak merusak (keimanannya).”
Lebih lanjut al-Syahrastani menyebutkan bahwa irja bisa diartikan menunda keputusan tentang status pelaku dosa besar sampai hari kiamat. Selain itu, arti “menunda” juga berlaku untuk menempatkan Ali pada urutan keempat dari yang semestinya pada urutan pertama untuk menjadi khalifah.[7]
Namun, dalam artikel kali ini, kita tidak akan lebih jauh membahas tentang pandangan teologi Abu Hanifah, dan dugaan bahwa dia adalah salah seorang penganut Murjiah. Ke depan, tulisan ini akan mengelaborasi lebih jauh tentang perkembangan mazhab Hanafi dan warisan yang ditinggalkannya untuk Dunia Islam. (PH)
Bersambung ke:
Catatan Kaki:
[1] Karim D. Crow, Abū Ḥanīfa Nu‘mān ibn Thābit, dalam Alexander Wain dan Mohammad Hashim Kamali (ed), The Architects of Islamic Civilisation (International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia, 2017), hlm 39.
[2] Lebih lengkap tentang Doktrin Rasional, lihat Ayatullah Muhammad Baqir Shadr, Falsafatuna, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Arif Maulawi (Rausyan Fikr Institute, 2013), hlm 18-22.
[3] M Khoirul Huda, Lc, “Perkembangan Mazhab Hanafi”, dari laman https://beritagar.id/artikel/ramadan/perkembangan-mazhab-hanafi, diakses 20 September 2019.
[4] Karim D. Crow, Loc.Cit.
[5] Ibid.
[6] Fauzan Saleh, Kita Masih Murji’ah: Mencari Akar Teologis Pemahaman Keagamaan Umat Islam di Indonesia (Jurnal Tsaqafah, Vol. 7, No. 2, Oktober 2011), hlm 227-228.
[7] Ibid.




