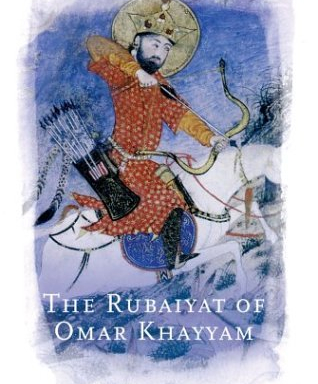“Pada tahun 1950-an, perusahaan-perusahaan minyak raksasa milik Barat yang disebut seven sisters begitu mendominasi Timur Tengah. Bahkan mereka dapat menggulingkan kekuasaan suatu negara.”
–O–
Proposal Frank Holmes untuk mengeksplorasi wilayah Arab, meskipun ditentang oleh pemerintah Inggris, pada akhirnya diterima dengan baik oleh bin Saud. Di tengah wilayah yang iklim dan ekonominya keras, untuk mendapatkan uang bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, bin Saud dan penguasa-penguasa lokal lainnya di sepanjang Semenanjung Arab senang bertemu siapa saja yang dapat membayar tunai sebagai imbalan atas hak untuk eksplorasi padang pasir mereka.
Namun sayang bagi Holmes – meskipun dia sudah menemukan tanda-tanda adanya minyak – dia tidak dapat menemukan penyokong dana di London. Ketika perusahaannya mulai kehabisan uang, dia memutuskan untuk mencoba peruntungan baru di Bahrain, yang saat itu merupakan protektorat Inggris.
Selain memiliki kemampuan handal untuk menemukan minyak, Holmes juga secara kepribadian memiliki perpaduan antara mempesona dan pandai menggertak. Di antara tahun 1922 sampai pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, Holmes disambut oleh para pemimpin Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait — di mana dia sukses besar — dan di Uni Emirat Arab.
Minyak dan Politik Timur Tengah
Setelah penemuan minyak di Persia (Iran pada zaman modern) pada tahun 1908 dan di Irak pada tahun 1927, tahun 1930-an terjadi gelombang besar kegiatan pencarian di Semenanjung Arab dan sekitarnya. Sejumlah besar minyak yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial ditemukan di Bahrain pada tahun 1932; di Kuwait dan Uni Emirat Arab pada tahun 1937; di Arab Saudi pada tahun 1938; dan di Qatar pada tahun 1939.
Masuk tahun 1950-an, tidak ada satu pun negara di kawasan Timur Tengah yang tidak merasa tidak puas (pada situsasi paling baik) atau tertipu (paling buruk) oleh kesepakatan yang mereka tandatangani. Di Iran, di mana minyak telah ditemukan jauh sebelumnya, ketidakpuasan justru muncul lebih awal.
Perwakilan dari pemerintah Iran – pada waktu itu masih dikenal sebagai Persia hingga tahun 1935 – menghabiskan sebagian besar tahun 1920-an dan awal 1930-an untuk bernegosiasi ulang dengan APOC (Perusahaan Minyak Anglo-Persia), sebelum menandatangani perjanjian baru pada tahun 1933. Kontrak baru ini memberikan bagian lebih besar dari keuntungan bagi pemerintah Iran, dan mengurangi ukuran konsesi perusahaan. Walaupun demikian, kontrak baru itu masih tetap sangat menguntungkan bagi APOC.
Kontrak baru itu sekarang memungkinkan para pejabat perusahaan untuk memilih di mana saja mereka dapat melakukan pengeboran, dan juga memperpanjang konsesi hingga 32 tahun. Dan yang paling sembarangan, kontrak itu membebaskan mereka dari semua bea impor dan bea cukai, yang mana sangat merugikan pemerintah. Pemerintah Iran dirugikan dengan hilangnya jutaan pendapatan yang tidak terhitung.
Pada tahun 1950, Iran mendapatkan 17% dari keuntungan penjualan minyak. Pada tahun berikutnya, 1951, parlemen Iran memutuskan untuk melakukan nasionalisasi cadangan minyak negara. Iran juga memilih negarawan yang sangat dihormati dan seorang pelopor nasionalisasi, Muhammad Mossadeq, untuk menjadi Perdana Menteri.[1]

Pada tahun 1953, Mossadeq harus membayar mahal atas sikapnya yang non-koordinatif dengan Barat dan ingin melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan minyak asing. Dalam sebuah skenario yang dirancang oleh CIA (Central Intelligence Agency) Amerika Serikat dan MI6 (Military Intelligence, Section 6) Inggris, Mossadeq, seorang negarawan populer, dan Perdana Menteri yang terpilih secara demokratis, digulingkan dari kekuasaan.
Peristiwa tersebut memberikan pesan yang sangat jelas bagi siapapun penguasa-penguasa di negara penghasil minyak di kawasan Timur Tengah: Jangan pernah bermain-main dengan gagasan nasionalisasi perusahaan minyak milik Barat.[2]
Setelah tahun 1953, tujuh perusahaan minyak raksasa mendominasi industri minyak dunia, mereka adalah Anglo Persian Oil Company/APOC (sekarang British Petroleum/BP), Gulf Oil (sebagian besar menjadi bagian dari British Petroleum dan bagian lainnya bergabung dengan Chevron), Standard Oil of California atau SoCal (Chevron hari ini), Texaco (kemudian menjadi bagian dari Chevron setelah merger), Royal Dutch Shell yang berkantor pusat di London, Standard Oil Company of New Jersey (Esso yang kemudian menjadi Exxon), dan Standard Oil Company of New York atau Socony (Mobil, yang kemudian bergabung dengan Exxon menjadi ExxonMobil).[3]
Tujuh perusahaan besar ini seringkali dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan. Namun dalam gelombang pencarian yang tidak bisa dikendalikan, negara-negara penghasil minyak mulai mencari-cari mitra lainnya yang dapat lebih menguntungkan. Hanya berselang 20 tahun kemudian, tujuh besar terpaksa bergabung dengan lebih dari 300 perusahaan independen dan 50 perusahaan milik negara. Cengkeraman yang dirasakan negara-negara Timur Tengah kini menjadi lebih longgar.[4] (PH)
Bersambung ke:
Kutukan Minyak bagi Timur Tengah (4): Masa Depan Timur Tengah
Sebelumnya:
Catatan Kaki:
[1] Eamon Gearon, Turning Points in Middle Eastern History, (Virginia: The Great Courses, 2016), hlm 276-277.
[2] Bethany Allen-Ebrahimian, “64 Years Later, CIA Finally Releases Details of Iranian Coup”, dari laman https://foreignpolicy.com/2017/06/20/64-years-later-cia-finally-releases-details-of-iranian-coup-iran-tehran-oil/, diakses 18 Juli 2018.
[3] “What are the Seven Sisters Oil Companies?”, dari laman https://www.financial-dictionary.info/terms/seven-sisters-oil-companies/, diakses 18 Juli 2018.
[4] Eamon Gearon, Ibid., hlm 277.