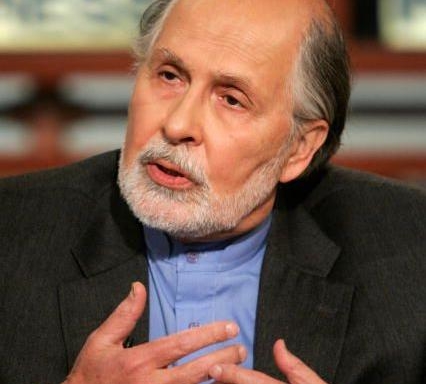Salah satu kisah favorit Kuntowijoyo adalah mengenai penolakan Nabi Muhammad untuk tetap tinggal di langit dalam peristiwa Isra’ Mi’raj.

Oleh Zainal Abidin Bagir[1]
Islamisasi Ilmu versus Pengilmuan Islam (2)
Dari pemaparan sejauh ini, perlu diperhatikan bahwa meski Kuntowijoyo menyebut pengilmuan Islam sebagai alternatif islamisasi ilmu, gagasan ini tak bisa semata-mata ditempatkan dalam rubrik “ilmu dan agama”. “Ilmu dan agama” biasanya berbicara tentang hubungan ilmu dan agama (misalnya, pertanyaan mengenai apakah keduanya dalam konflik atau harmoni? Bagaimana mengintegrasikan keduanya? Perlukah ilmu menjadikan agama sebagai salah satu sumbernya?) Pengilmuan Islam sedikit banyak memang berbicara tentang hubungan ilmu dan agama, tapi juga tentang bagaimana Islam sebagai sebuah agama mesti dihayati Muslim kontemporer. Untuk yang belakangan ini, contoh-contoh terbaiknya justru berada dalam wilayah pembicaraan tentang posisi Muslim dalam ranah sosial-politik Indonesia.
Pertama, melalui analisis tiga periode yang diajukannya, pengilmuan Islam berusaha menjelaskan posisi umat Islam dalam panggung sosial politik. Kedua, tak berhenti pada memberikan penjelasan, pengilmuan Islam juga merupakan saran kemana umat Islam mesti bergerak. Ketiga, secara lebih umum, pengilmuan Islam dapat dianggap sebagai suatu teori sosial mengenai gerak sejarah umat Islam. Di sinilah tampaknya kedua makna pengilmuan Islam bertemu: karakter ilmu sosial yang digagas Kunto tak sekadar berhenti sebagai ilmu (yang fungsi utamanya adalah menjelaskan fenomena/peristiwa), tapi punya ‘ambisi’ melakukan transformasi.
Dalam sebuah tulisannya, Kuntowijoyo menyinggung tentang gagasan teologi transformatif yang dikemukakan Moeslim Abdurrahman, dan dia mencoba memahami mengapa gagasan ini sulit diterima kebanyakan Muslim (ISI, 88-91).[2] Sebabnya, bagi mereka teologi adalah sesuatu yang sudah selesai—tak perlu ada teologi baru. Dengan pembahasan di paragraf sebelum ini, kita bisa memahami mengapa kemudian dalam kesempatan itu Kunto mengajukan “ilmu sosial profetik” sebagai alternatif bagi “teologi transformatif”. “Ilmu” bisa menjadi alternatif bagi “teologi” ketika keduanya dipahami secara lebih luas.
Di satu pihak, teologi dipahami bukan sebagai sekumpulan doktrin tentang masalah-masalah ketuhanan saja, tapi juga keinginan menyikapi kenyataan empiris menurut perspektif ketuhanan (ISI, 89); dengan kata lain, teologi adalah juga cara menafsirkan realitas empiris, dan karenanya dinamis. Di pihak lain, ilmu dipahami sebagai tak bebas-nilai (tak berpihak), tapi mengandung aspirasi transformasi sosial dalam bentuk cita-cita profetik.
Pertanyaan berikutnya: apakah ketakbebasnilaian itu tak bertentangan dengan keinginan untuk bersikap objektif (melakukan objektifikasi)? Satu penjelasan yang bisa diajukan adalah, ketika Kunto menyebut objektifitas, yang lebih ingin ditekankannya adalah karakter ilmu yang objektif, dalam artian pengalaman publik yang bisa dipahami/diverifikasi/dihayati bersama-sama oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat (dan karenanya bisa mengantarkannya ke universalitas). Bersifat objektif adalah mengambil jarak dari subjektifitas pengamat. Filsafat ilmu kontemporer telah cukup menunjukkan bahwa “objektifitas murni” jelas tak mungkin, dan karenanya sebagian filosof kini lebih senang menggunakan istilah trans-subjektif. Tapi ujung-ujungnya sama: ada kesepakatan mengenai realitas di antara komunitas keilmuan.
Sementara itu, keberpihakan (ketakbebasnilaian) adalah persoalan lain. Kuntowijoyo melihat bahwa sementara ilmu-ilmu sosial modern mengklaim bersifat bebas-nilai, sesungguhnya dalam banyak kasus ada keberpihakan atau kepentingan yang tersembunyi. Beberapa contoh yang bisa diberikan adalah ilmu antropologi awal yang berpihak kepada kepentingan kolonial; ilmu ekonomi (neo-)liberal yang lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal;[3] ilmu mengenai sumber energi yang lebih dikembangkan ke teknologi tertentu (misalnya, energi fosil dan nuklir, sembari mengabaikan energi surya); dan sebagainya (contoh-contoh lain diberikan dalam ISI, 57).
Dalam kasus-kasus tersebut, selalu ada beberapa pilihan yang tersedia dan harus diambil salah satunya; ini adalah proses pemilihan etis. Sejauh ini, kalaupun pertimbangan etis diikutsertakan, sifatnya hanya sebagai imbuhan eksternal, tak inheren dalam ilmu itu sendiri. Yang diupayakan Kuntowijoyo adalah memasukkan pertimbangan-pertimbangan etis itu ke batang tubuh ilmu. Pada akhirnya, ilmu yang lahir bersama etika tidak boleh partisan, namun harus bermanfaat untuk manusia seluruhnya (ISI, 57). Ilmu yang integralistik tak akan mengucilkan Tuhan ataupun manusia.
Sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa perbedaan pengilmuan Islam dengan islamisasi ilmu terletak dalam beberapa hal. Pertama, pengilmuan Islam lebih terbuka terhadap ilmu-ilmu sekular. Kedua, islamisasi ilmu lebih bersifat reaktif dan normatif (mengembalikan konteks ke teks) dan memberikan perhatian lebih rendah pada kondisi aktual empiris. Ketiga, pengilmuan Islam (dalam wujudnya sebagai ilmu sosial profetik) lebih menekankan pada berkeinginan untuk memberikan arah etis bagi transformasi kondisi empiris itu.
Penutup
Kuntowijoyo adalah suatu sosok multidimensional—seorang ilmuwan sosial, sejarawan, dan sastrawan. Dengan mengangkat gagasan pengilmuan, dia ingin menekankan pada sifat ilmu yang objektif (atau trans-subjektif), yang publik, melampaui individu. Kekurangan ilmu yang dilihatnya adalah keterpisahannya dari etika, dan menghindari keberpihakan. Ini dicoba diatasinya dengan mengintegrasikan ilmu modern dengan cita-cita profetik yang bersumber dari agama.
Dengan ini kita bisa memahami “ambisi”-nya melakukan outreach ke sebanyak mungkin orang, tanpa mengenal batasan-batasan identitas. Perhatian utamanya adalah kemanusiaan, dan semua aktifitas, termasuk aktifitas beragama, mesti ditujukan untuk melayani kepentingan umat manusia. Tak mengherankan jika dia sempat menolak ajakan malaikat untuk terbang ke langit, seperti disampaikan oleh puisi yang menjadi motto seminar ini. Sebagaimana ditunjukkan Nabi Muhammad, hatinya ada bersama manusia yang hidup di dunia ini, khususnya kaum yang menderita.
Salah satu kisah Nabi Muhammad yang tampaknya menjadi favoritnya dan kerap disampaikannya adalah kisah yang disampaikan penyair-filosof Muhammad Iqbal mengenai penolakan Nabi untuk tetap tinggal di langit dalam peristiwa Isra’ Mi’raj. Dia ingin kembali ke bumi untuk melaksanakan cita-cita profetiknya. Solidaritas kemanusiaan universal inilah kiranya yang menjadi pesan utama dakwah Kunto, dan yang sulit ditolak bahkan oleh kaum pasca-modernis yang mencurigai setiap klaim universalitas.
Selesai.
Sebelumnya:
Catatan
Kaki:
[1] Zainal Abidin Bagir, Ph.D, saat ini beliau merupakan Direktur Program Pasca Sarjana Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gajah Mada. Tulisan ini pernah disampaikan beliau dalam diksusi tentang pemikiran Kuntowijoyo yang diadakan Masyarakat Yogyakarta untuk Ilmu dan Agama (MYIA) dan Badan Koordinasi Mahasiswa Sejarah (BKMS) UGM, 26 Mei 2005, di UGM. Atas izin penulis, Redaksi Gana Islamika diperkenankan untuk menerbitkannya.
[2] ISI: Islam Sebagai Ilmu, Jakarta: Teraju-Mizan, Juni 2004.
[3] Satu contoh untuk ini adalah gagasan ekonomi Pancasila yang dikembangkan Alm. Prof. Mubyarto. Secara singkat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi rakyat; ekonomi yang meletakkan kesejahteraan rakyat, bukan pemilik modal, pada prioritas pertama. Keberpihakan kepada rakyat dalam hal ini adalah suatu nilai yang perlu diajukan tidak secara normatif, tapi dengan cara mengobjektifkannya: yaitu, meyakinkan orang lain secara argumentatif dan menggunakan data-data empiris bahwa ekonomi yang sehat harus meletakkan kepentingan rakyat pada prioritas pertama. Jadi, di sini ada pilihan etis, dan ekonomi, menurut ilmu profetik, tak seharusnya bersikap netral. Keinginan untuk netral seringkali justru berarti keberpihakan tersembunyi.