Filsafat perennial adalah nama lain dari metafisika Islam sebagaimana dipahami Nasr. Meskipun disebut “filsafat”, warna mistikalnya amat kental.
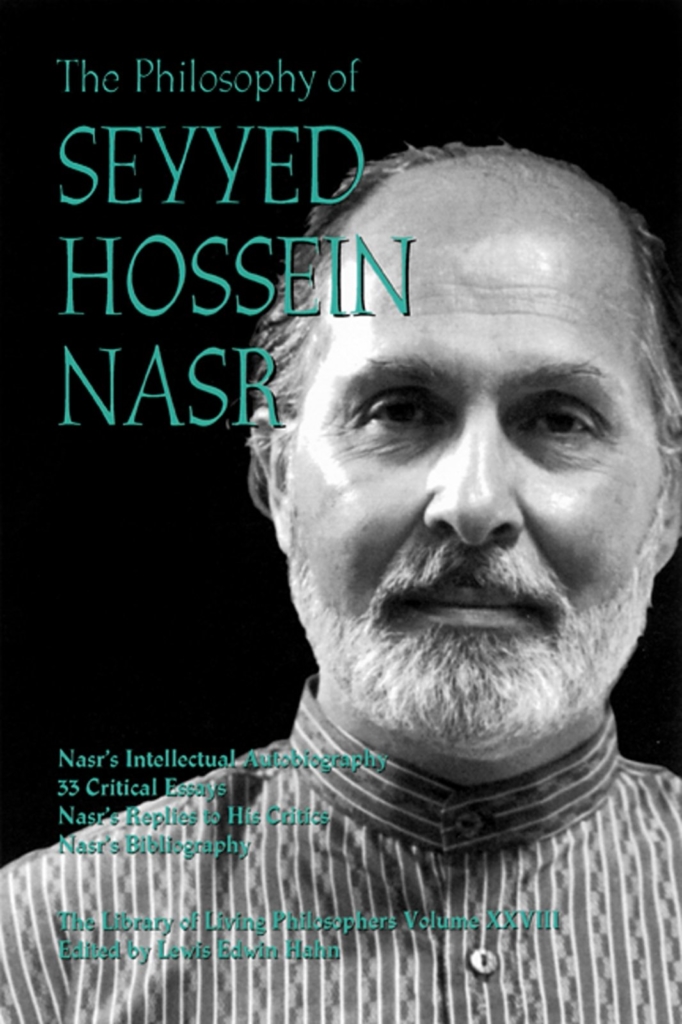
Oleh Zainal Abidin Bagir[1]
Resensi atas buku: L. E. Hahn, R. E. Auxier, L. W. Stone, Jr., eds., The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr (The Library of Living Philosophers, Vol. XXVII), Open Court, Illinois, AS, 2001,1001+xviii hal.
“Benarkah filsafat perennial adalah filsafat ketinggalan jaman?” demikian seorang kontributor buku ini menggambarkan reaksi umum terhadap jenis filsafat yang dikembangkan Seyyed Hossein Nasr. Dalam dunia Barat saat ini yang didominasi oleh filsafat analitik dan kontinental, perennialisme memang tak mendapat tempat. Karena itu, cukup mengherankan—dan merupakan penghargaan tersendiri—bahwa Nasr bisa terpilih untuk serial Library of Living Philosophers ini.
Sejak diterbitkannya nomor pertama serial ini pada 1939, Nasr adalah filosof non-Barat kedua (S. Radhakrishnan yang pertama). Sebagai filosof Muslim, dialah satu-satunya. Dengan itu ia dijajarkan bersama John Dewey, Bertrand Russell, Einstein, Carnap, Popper, Sartre, Quine, Ricoeur, Gadamer, dan belasan nama masyhur lainnya.
Berbeda dari mereka, Nasr sendiri dengan yakin menempatkan dirinya berhadap-hadapan dengan modernisme, sebagai “suatu filsafat yang premis dan asumsi-asumsinya saya tolak dan saya tentang selama empat dasawarsa terakhir ini.” Tak mengherankan kalau pertanyaan yang kerap muncul dalam buku ini adalah tentang relevansi dan keabsahan hikmah perennis-nya di dunia (pasca-) modern.
Filsafat perennial adalah nama lain dari metafisika Islam sebagaimana dipahami Nasr. Ia juga menyebutnya sebagai ilmu tentang Kenyataan Ultim, yang ada dalam semua agama atau tradisi spiritual sejak awal sejarah intelektual manusia hingga kini. Meskipun disebut “filsafat”, warna mistikalnya amat kental.
Buku ini terdiri dari tiga bagian: otobiografi intelektual, esai-esai tentang pemikiran Nasr yang diikuti oleh tanggapannya, dan bibliografi lengkap karya Nasr. Huston Smith, salah satu dari 29 penyumbang di buku ini, mengawali dengan mendaftar beberapa karakter filsafat perennial yang menyebabkannya sulit tumbuh dalam iklim filsafat modern.
Pertama, perenialisme adalah suatu metafisika yang mengklaim memiliki akses langsung melalui fakultas intuitif kepada Sang Kebenaran/Kenyataan, terkait dengan agama, dan bersifat tradisional. Padahal, filsafat modern sejak awal sudah menentang ketiga hal ini. Namun bagi Nasr, tetap adanya kehausan intelektual-spiritual manusia modern yang tak bisa dipenuhi filsafat sekular menunjukkan masih adanya tempat bagi perennialisme.
Gagasan adanya Kebenaran, dengan “K” besar, juga menentang arus relatifisme yang dianggap sebagai temuan penting filsafat kontemporer. Lebih jauh, Mehdi Aminrazavi, murid Nasr, mempertanyakan sulitnya memverifikasi klaim-klaim kaum perennialis yang berasal dari “ilmu intuitif langsung” tentang Kebenaran.
Bagi Nasr, relatifisme dan pertanyaan tentang verifikasi hanya muncul dari kaum rasionalis yang tak mengakui keabsahan akal intuitif (intellect) sebagai akal yang lebih tinggi daripada akal diskursif/rasional (reason). Tugas Nasr berikutnya, yang sayangnya tak dilaksanakannya dengan cukup baik, adalah menjustifikasi intelek ini tanpa lebih dulu mengasumsikan keberadaannya.
Nasr kemudian, mengikuti filosof besar Suhrawardi, mengingatkan bahwa klaim-klaim para ilmuwan sekalipun (dalam mekanika kuantum, misalnya) tak dapat diverifikasi orang awam. Ada prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya memahami matematika tingkat tinggi, yang hanya bisa diperoleh setelah studi bertahun-tahun.
Demikian pula dengan “klaim” kaum perennialis, yang verifikasinya menuntut persiapan intelektual-spiritual yang memadai. Namun, sejauh mana analogi ini bisa dipegang? Apakah, misalnya, ada kemampuan prediktif serupa dalam ilmu intuitif?
Dalam mekanika kuantum, para ilmuwan yang memiliki interpretasi berbeda-beda sekalipun bisa mencapai konsensus setidaknya dalam hal prediksi. Sementara, seperti ditunjukkan Aminrazavi, klaim-klaim perennialis kerap bertentangan. Dia memberikan contoh pandangan evolusionis Teilhard de Chardin, yang mengklaim mendapatkan pengalaman ilahiah, tapi lalu dikritik oleh Nasr, yang memiliki klaim serupa.
Jawaban Nasr: “selalu ada kesepakatan dalam hal-hal yang menyangkut prinsip”—misalnya prinsip tauhid—meskipun ekspresinya mungkin berbeda-beda. Namun jika dibatasi pada prinsip amat umum seperti itu, apakah lalu pemikir Muslim seperti Sayyid Qutub dan Fazlur Rahman, misalnya, yang tampaknya akan menentang banyak aspek perennialisme, bisa disebut juga sebagai perennialis? []
Bersambung ke:
Catatan Kaki:
[1] Zainal Abidin Bagir, Direktur Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Pascasarjana, UGM. Seri artikel Seyyed Hossein Nasr yang ditulis oleh Zainal Abidin Bagir ini tadinya berasal dari tiga artikel yang ditulis oleh beliau di Koran Tempo (Suplemen Ruang Baca) pada 11 Februari 2002. Atas izin dari yang bersangkutan, Redaksi Gana Islamika diperkenankan untuk menerbitkan kembali tulisan ini.




