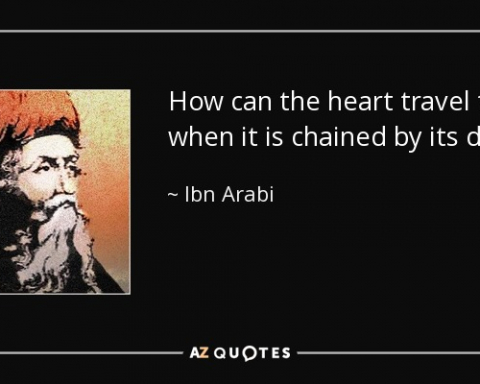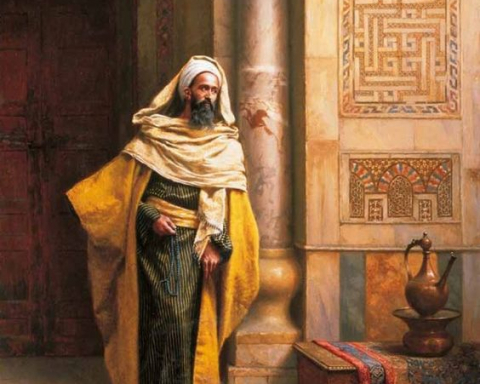Oleh Mi’raj Dodi Kurniawan[1]
“Bahkan sebelum menjadi Nabi, tanda-tanda sebagai sosok pengubah peradaban telah melekat kepadanya, yaitu dengan diberikannya gelar Al-Amiin dan As-Saadiq.”
–O–

Pada dasarnya, kendati kebudayaan dan peradaban dibangun oleh masyarakat, namun jika menyoal peletak awal kebudayaan dan peradaban itu, maka hal itu harus dan akan sampai hanya pada satu sosok atau beberapa gelintir individu pencetus dan penggeraknya. Dalam konteks Peradaban Islam Klasik, tidak bisa tidak, sosok tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan beberapa gelintir individu lainnya ialah para sahabat dan para penerusnya.
Jika ditelisik lagi, maka para sahabat pun – sebenarnya – dipengaruhi Nabi, sehingga jika harus menelusuri ke awal gerakan Islam, hal itu akan bermuara kepada individu Nabi. Oleh sebab itu, bukan hanya keniscayaan, melainkan pula akan menjadi menarik untuk menyingkap identitas Nabi Muhammad. Sebab, figur agung ini tidak hanya membawa, tetapi juga merupakan individu pertama yang mendakwahkan risalah Islam.
Muhammad bin Abdullah merupakan keturunan suku Quraisy, yaitu suku terbesar dan berpengaruh di Mekkah (di wilayah selatan jazirah Arab). Beliau sudah yatim dan piatu sejak belia. Sewaktu masih kanak-kanak, beliau pernah disusui Aminah Zuhriyah (ibu kandungnya), Halimah As-Sa’diyyah dan Tsuwaibah Al-Aslamiyyah. Kemudian, pasca ditinggal wafat ayah dan ibunya, Muhammad belia tinggal bersama Abdul Muthalib (kakek kandungnya). Sesudah Abdul Muthalib wafat, beliau tinggal bersama Abu Thalib (pamannya dari pihak ayah). Lalu, sejak remaja hingga masa muda, Muhammad bekerja sebagai pedagang.
Suatu saat, dalam karirnya sebagai pedagang, Muhammad menjalankan misi perdagangan untuk Khadijah (w. 619 M), seorang janda kaya Mekkah, ke Suriah. Perjalanan ini bukan hal baru, sebab Muhammad pernah menjalaninya semasa kecil bersama pamannya, Abu Thalib. Lalu, Khadijah mengagumi kejujuran beliau, sehingga meminangnya sebagai suami. Saat itu, usia Muhammad sekitar 25 tahun sedangkan Khadijah sekitar 40 tahun. Lima belas tahun kemudian, ketika berusia sekitar 40 tahun, Muhammad melanjutkan perniagaan bersama Khadijah dan tak menikah lagi hingga istrinya ini wafat pada saat usia Nabi sekitar 50 tahun.[2]
Beberapa waktu setelah menikahi Khadijah, Muhammad secara teratur pergi ke Gua Hira yang terletak tak jauh di sebelah utara Mekah. Keluhuran budi pekerti mendorongnya melakukan tahannuts yang biasa diartikan sebagai tabarrur, melakukan perbuatan bajik (birr) dengan memberi makan fakir miskin, atau ta‘abbud, beribadah, atau keduanya, yakni tabarrur dan ta‘abbud ke gua itu untuk beberapa hari dan terkadang sampai beberapa minggu.[3]
Selama dalam masa tahannuts, Muhammad merenung secara mendalam. Beberapa hal yang direnungkannya adalah mengenai Tuhan, Pencipta yang Mutlak dan Pemelihara alam semesta, dan makhluknya, terutama tentang masalah-masalah kemasyarakatan: ketimpangan sosial-ekonomi, praktik-praktik niaga para pedagang kaya yang eksploitatif dan amoral, serta cara penghamburan kekayaan yang tidak bertanggung jawab manakala dikaitkan dengan kenestapaan fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang tertindas, seperti tercermin dalam praktik kehidupan masyarakat Quraisy.[4]
Proses batiniah berupa pengalaman religio-moral tersebut mencapai puncaknya di suatu malam yang belakangan diperingati Muslim sebagai “malam keputusan” (laylatu-l-qadr). Dikisahkan, sewaktu Muhammad sedang tenggelam dalam relung renungan terdalam di Gua Hira, beliau diseru Utusan Wahyu, Jibril, kepada Risalah Tuhan. Beliau melihat Jibril pada suatu visi (ru’yah) di “ufuk tertinggi”. Tatkala mengalami ledakan spiritual yang tiba-tiba, Muhammad merasa pasif secara total. Lalu dia pulang dalam keadaan menggigil bersimbah keringat, dan mengisahkan pengalaman batinnya kepada istrinya.[5]
Khadijah menenangkannya dengan membenarkan kesejatian pengalaman penerimaan Wahyu tersebut, karena dalam kenyataannya, Muhammad, merupakan orang yang baik dan tak mungkin dirasuki ruh jahat. Setelah itu, Muhammad tidak pernah lagi pergi dan ber-tafakur di Gua Hira. Melainkan, sosok al-Amiin ini mulai menindaklanjuti misi historisnya sebagai utusan Allah bagi umat manusia.[6] Beliau bukan hanya mulai mendeklarasikan kenabiannya, tetapi juga mulai mengajarkan Islam sesuai Wahyu.
Menurut riwayat, pengalaman pertama kenabian Muhammad terjadi saat beliau berusia sekitar 40 tahun atau lebih sedikit, kira-kira 13 atau 15 tahun sebelum Hijriah. Secara tidak langsung hal ini dikonfirmasi Q.S. Yunus ayat 16, “…Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya (sebelum pewahyuan Al-Qur’an)…” artinya, ketika diangkat menjadi Nabi, Muhammad bukan lagi anak muda berusia remaja, melainkan berada dalam usia matang untuk memperoleh pengalaman kenabian.[7]
Muhammad tidak pernah berkeinginan menjadi Nabi atau menyiapkan diri untuk itu. Hal ini dikemukakan dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Namun, secara alamiah, dapat dikatakan bahwa beliau telah menyiapkan diri. Sebab, sejak kecil beliau memiliki kepekaan intensif dan alami atas masalah-masalah moral yang dihadapi manusia. Kepekaan ini kian tajam saat beliau yatim piatu dalam usia yang masih sangat belia. Beliau tentu saja tidak berupaya secara sadar untuk menambah kemampuan-kemampuan alaminya melebihi manusia-manusia lain, sehingga ketika seluruh faktor alami itu berkolaborasi menuju suatu tujuan yang sangat kuat, maka hal ini harus dikembalikan kepada Allah SWT.[8]
Ketika kaum pagan Arab menyoal penunjukannya menjadi Nabi dan mempertanyakan kenapa Wahyu Ilahi tidak diturunkan kepada ‘orang besar’, yakni orang kaya dan berpengaruh di Mekkah dan Thaif karena Muhammad dianggap bukan orang kaya dan berpengaruh waktu itu (Q.S. Az-Zukhruf: 31), Al-Qur’an menerangkan jawaban religius dan naturalistik. Secara religius, Allah SWT mengajukan jawaban-Nya dalam bentuk pertanyaan retorik, “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?” (Q.S. Az-Zukhruf: 32). Sementara jawaban naturalistik diterangkan Q.S. Al-An’am ayat 124, “…Allah mengetahui dimana menempatkan tugas kerasulan-Nya…”[9]
Mulanya, pasca diangkat menjadi Utusan Allah SWT, Muhammad mendakwahkan Islam secara pribadi kepada keluarga dan teman-teman dekatnya. Istrinya (Khadijah) dan Ali ibn Abi Thalib (keponakannya, w. 661 M) adalah orang-orang pertama yang membenarkan kerasulannya. Selain dua orang tadi, umumnya, para pengikut awal Nabi berasal dari kalangan tertindas yang tidak memiliki posisi sosial dan politik yang penting, meski beberapa diantaranya pedagang kaya – seperti Abu Bakr al-Shiddiq (w. 634 M) – dan orang-orang yang mengalami fermentasi keagamaan – seperti Utsman bin Maz’un.
Namun, aristokrasi pedagang Mekkah, yang berpengaruh besar di masyarakat, menolak dakwahnya dan mengerahkan pengaruh mereka untuk membendungnya. Mereka memandang dakwah Islam sebagai ancaman pada tradisi “bapak-bapak kami,” yaitu politeisme (keyakinan pada banyak tuhan atau menuhankan banyak hal), yang darinya mereka beroleh keuntungan material dan keistimewaan sosial-ekonomi. Maka, sekitar dua tahun pasca pewahyuan pertama, saat Nabi menyampaikan pesan-pesan Ilahi secara terbuka pada khalayak ramai, timbul oposisi aktif terhadap Islam, dan para pengikut Nabi yang tak begitu kuat, mengalami penindasan keji.
Yang menarik, seakan-akan tanda-tanda kepribadiannya melegitimasi status kenabiannya kelak, sebelum menjadi Nabi, Muhammad telah memperoleh dua gelar dari suku Quraisy: Pertama, Al-Amiin (orang yang dapat dipercaya) yang mengindikasikan kejujuran dan kepekaan moral tinggi Muhammad.[10] Kedua, As-Saadiq (yang benar). Dan setelah masa kenabian, para sahabatnya memanggil beliau Rasul Allah (utusan Allah) ditambah kalimat Shalallaahu Alaihi Wasallam (semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya).
Akhirnya, dalam konteks perubahan kebudayaan dan peradaban Islam Klasik di dunia, atau setidaknya di Madinah dan Mekkah, sulit dipungkiri bahwa di sana terdapat peran besar visi spiritualitas dan keseriusan Nabi untuk mewujudkannya. Di tangannya, Wahyu tidak hanya diinternalisasi, melainkan juga disebarkan sehingga mempengaruhi keluarga, para sahabat, dan masyarakat. Akibatnya, umat Islam Klasik bukan hanya memiliki kebudayaan yang lebih baik, tetapi juga mencetak peradaban yang luar biasa.
Bersambung ke:
Spiritualitas, Minoritas Kreatif, dan Peradaban Islam Klasik (4): Visi Spiritualitas Islam
Sebelumnya:
Spiritualitas, Minoritas Kreatif, dan Peradaban Islam Klasik (2): Madinah al-Nabi
Catatan Kaki:
[1] Ketua Bidang Litbang KAHMI Cianjur, Sejarawan UPI Bandung, dan Penulis essay-essay tentang Keislaman di berbagai media Nasional.
[2] Taufik Adnan Amal. 2011. Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi. Hlm 31.
[3] Ibid.
[4] Ibid., hlm 31-32.
[5] Ibid., hlm 32.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid., hlm 32-33.
[9] Ibid., hlm 33.
[10] Ibid., hlm 31.