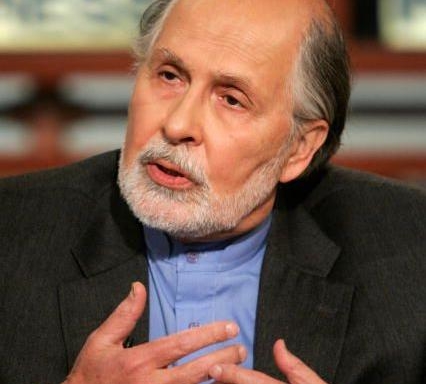Bagi kaum rasionalis kebenaran-kebenaran dapat dicapai tanpa melalui medium kenabian/kitab suci.

Oleh Zainal Abidin Bagir[1]
Dua pra-Anggapan Filosofis: Rasionalisme dan Pluralisme
Beberapa paragraf terakhir dalam artikel sebelumnya menyiratkan beberapa pra-anggapan filosofis Kuntowijoyo. Setidaknya ada dua hal yang bisa dicatat di sini: (1) Dalam polarisasi mazhab rasionalis dan tekstualis, posisi Kuntowijoyo ada dalam “kubu” pemikiran Islam yang lebih rasionalis; (2) Dia meyakini bahwa semua agama memiliki keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang serupa.
(1) Sejak masa awal pemikiran Islam, ada perdebatan di kalangan pemikir Muslim yang membagi mereka ke mazhab-mazhab rasionalis (mu’tazili) dan tekstualis. Kaum tekstualis, misalnya, memahami bahwa sesuatu perbuatan bersifat baik atau buruk karena ia diperintahkan atau dilarang oleh Tuhan; kaum rasionalis, sebaliknya, melihat bahwa sesuatu perbuatan dilarang atau diperintahkan oleh Tuhan karena perbuatan tersebut bersifat baik atau buruk. Yang pertama menaruh kesetiaannya pertama-tama pada teks; yang kedua terutama melihat adanya nilai inheren yang objektif dalam agama. Ini jelas memberi ruang yang cukup besar bagi manusia untuk memikirkan rasionalitas teks. Bahkan, bagi kaum rasionalis yang cukup “ekstrem”, karena kebaikan tersebut bersifat objektif, itu berarti ia accessible untuk pikiran manusia. Implikasinya, kebenaran-kebenaran tersebut dapat dicapai tanpa melalui medium kenabian/kitab suci (inilah salah satu yang ingin ditunjukkan dalam novel populer Hayy ibn Yaqzhan).
Kunto saya kira tak ingin bergerak sejauh itu. Namun secara teoretis, keyakinannya akan rasionalitas Islamlah yang memungkinkannya menggagas objektifikasi Islam. Sementara kaum tekstualis selalu ingin kembali kepada teks; kaum rasionalis seperti Kuntowijoyo berangkat dari teks namun kemudian bergerak jauh untuk menjelajahi dunia. Yang pertama biasanya bersifat amat normatif, yang kedua empiris. Inilah yang di bawah nanti akan ditunjukkan sebagai salah satu pembeda pengilmuan Islam dari islamisasi ilmu.
Ciri utama periode ilmu adalah aktifitas objektifikasi Islam agar “Islam jadi rahmat untuk semua” (ISI, 50). Gagasan-gagasan normatif Islam ditampilkan sebagai nilai-nilai universal, bersifat publik, dan dijustifikasi secara rasional. Nilai-nilai tersebut layak diterima bukan karena ia berasal dari Islam; berasal dari Islam atau tidak, itu tak penting lagi. Yang penting adalah bahwa nilai-nilai itu bisa ditunjukkan sebagai mengandung kebaikan pada dirinya sendiri, sehingga sumber nilai-nilai itu menjadi tak penting; yang penting adalah kemampuan menjustifikasinya secara rasional, demi mempersuasi sebanyak mungkin orang untuk menerimanya.
Sebagai hasilnya, “Meyakini latar belakang agama yang menjadi sumber ilmu atau tidak, tidak menjadi masalah, ilmu yang berlatar belakang agama adalah ilmu yang objektif, bukan agama yang normatif,” (ISI, 57). Objektifikasi ilmu adalah ilmu dari orang beriman untuk seluruh manusia, tanpa mengenal agamanya, non-agama, bahkan anti agama. “Pendeknya, dari orang beriman untuk seluruh manusia,” (ISI, 58).
(2) Hal yang persis sama berlaku untuk agama-agama lain, yang bagi Kunto juga perlu melakukan objektifikasi agar manfaatnya dirasakan semua orang. Ini karena dia tampak yakin benar bahwa semua agama memiliki keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang serupa. Untuk ini, cukuplah mengutip pernyataannya yang paling jelas dan eksplisit dalam tulisan terakhirnya “Maklumat Sastra Profetik” di Horison (Mei 2005).[2] Sebagai sarana untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi, yang melampaui keterbatasan akal manusia,
“… Kitab Suci yang satu tidak lebih tinggi daripada Kitab Suci lainnya. Mereka sejajar. Islam mengajarkan (Al-Quran, 3: 64) tentang adanya kalimah sawa’ (titik temu, konsensus, common denominator). Tidak ada pertentangan tentang hal-hal yang fundamental, meskipun ada perbedaan dalam detailnya. Maka sekalipun dalam maklumat ini saya hanya mengemukakan ajaran dari satu Kitab Suci saja, saya yakin dapat mewakili semua Kitab Suci lainnya. Sebab, maklumat ini hanya akan membicarakan hal-hal yang ada titik temunya, dan yang tidak kontroversial,” (MSP, 8).
Kalimat terakhir perlu digarisbawahi: bagi Kunto, keberpihakan pada etika profetik (yang dijabarkannya menjadi humanisasi, liberasi, dan transendensi) adalah hal-hal yang tak kontroversial, bisa diterima semua orang (kecuali mungkin nilai ketiga, yang bermakna hanya bagi kaum beragama). Bagi Kunto yang Muslim, inspirasi mengenai ketiga cita-cita profetik ini didapatnya dari Alquran 3: 110 (“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Tuhan”). Kunto membaca ayat ini sebagai perintah untuk meperjuangkan humanisasi (amar ma’ruf), liberasi (nahi munkar), dan transendensi (beriman kepada Tuhan). Tanpa melakukan kajian lebih jauh, tampaknya tak sulit menemukan cita-cita profetik yang serupa di agama-agama lain.
Dalam tulisan terakhirnya, “Maklumat Sastra Profetik”, dia menjabarkan agenda etika profetik itu secara lebih terinci. Yang pertama, adalah melawan kecenderungan dehumanisasi (dalam wujud manusia mesin, manusia massa, dan budaya massa). Agenda liberasi adalah pembebasan masyarakat dari penindasan politik dan negara, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan gender. Agenda transendensi adalah “menghidupkan kembali” Tuhan yang telah dibunuh oleh beberapa aliran filsafat Barat (MSP, 11-16).
Bersambung….
Sebelumnya:
Catatan
Kaki:
[1] Zainal Abidin Bagir, Ph.D, merupakan Direktur Program Pasca Sarjana Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gajah Mada. Tulisan ini pernah disampaikan dalam diksusi tentang pemikiran Kuntowijoyo yang diadakan Masyarakat Yogyakarta untuk Ilmu dan Agama (MYIA) dan Badan Koordinasi Mahasiswa Sejarah (BKMS) UGM, 26 Mei 2005, di UGM. Atas izin penulis, Redaksi Gana Islamika diperkenankan untuk menerbitkannya.
[2] “Maklumat Sastra Profetik”, Horison, Mei 2005, 8-19. Selanjutnya dalam running notes akan disingkat menjadi MSP.