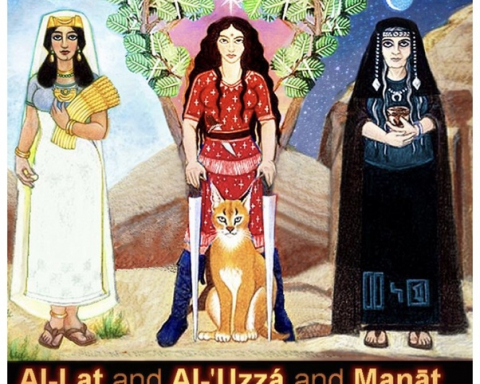Pertempuran tanpa jedah antara tentara akal dan tentara kejahilan, adalah narasi yang membentuk sejarah kerajaan jiwa. Pemenangnya, akan mengusai iradah (kehendak), yang merupakan tahap paling awal bagi pelaku suluk, lantaran ia mendahului semua tindakan. Para sufi menyebut pemula dalam suluk dengan murid, yakni orang yang mempunyai kehendak dan kemauan.

Bayangkan bila keadaan jiwa itu seperti tubuh: diperlukan syarat-syarat tertentu agar ia bisa hidup sehat dan berkembang secara layak. Oksigen, makanan, minuman dan sebagainya adalah keniscayaan secara fisikal. Dalam keadaan minus syarat-syarat tersebut, tubuh akan mengalami keloyoan, kelesuan, kerusakan, dan bahkan kematian. Bedanya, keloyoan, kerusakan, dan bahkan kematian jiwa tidak mengganggu kehadiran dan keberadaan fisik manusia. Seringkali penderita (subject) melalui keadaan semacam ini dengan santai dan rileks.
Dalam kamus para sufi, jiwa disebut dengan “nafs”. Bagi para sufi, jiwa adalah lahan subur dan land of opportunities bagi perkembangan dan penyempurnaan berbagai potensi manusia: syahwat (hawa nafsu); khayal (imajinasi); amarah (ghadhab); dan akal (‘aql). Keempat potensi ini bekerja sesuai dengan perintah kehendak (iradah) yang bersumber pada ruh (spirit). Dalam bahasa Barat, spirit sering disalingtukarkan dengan semangat (the will to live) yang menjadi dasar kehidupan–atau elan vitale menurut istilah Henri-Louis Bergson. Apa pun hakikat ruh itu, yang pasti dari situlah kehendak manusia berasal.
Kehendak manusia bebas menggunakan dan memerintah keempat potensi jiwa tersebut untuk mencapai apa yang diinginkannya. Apakah itu kesempurnaan, kebahagiaan, dan ketenangan maupun sebaliknya. Atau percampuran dari kesemuanya, sehingga menghasilkan suatu kesempurnaan, kebenaran, kebahagiaan, dan ketenangan yang sama sekali semu. Memperebutkan kehendak adalah pertarungan hidup-mati antara keempat potensi tersebut dalam sejarah kerajaan jiwa.
Al-Qusyayri menyebut iradah sebagai tahap paling awal bagi pelaku suluk, lantaran ia mendahului semua tindakan. Tanpa kehendak takkan ada tindakan, sama seperti halnya tanpa niat takkan ada peribadatan. Para sufi menyebut pemula dalam suluk dengan murid, yakni orang yang mempunyai kehendak dan kemauan.[1]
Dalam sejarah pergolakan jiwa, akal kerap kali dalam posisi yang terdesak. Selain karena kerjasama alamiah yang saling menguntungkan antara syahwat, amarah, dan khayal, ajakan akal untuk mencari hakikat kesempurnaan, kebenaran dan kembali kepada Tuhan sering terkubur oleh sensasi dan rangsangan dunia luar. Keintiman manusia dengan dunia yang menggoda, menipu dan terbatas ini kerap memperlemah posisi akal budi—lazim juga disebut juga dengan hati nurani—dalam jiwa.
Dominasi syahwat atas jiwa akan mentransformasi manusia menjadi binatang-binatang yang rakus, tamak, posesif. Syahwat akan mengerahkan energi manusia untuk memuaskan hasrat-hasratnya. Begitu satu hasrat terpuaskan, hasrat-hasrat baru bermunculan dengan daya desak pemuasan yang lebih besar. Rentetan hasrat itu akhirnya menjadi “tuhan-tuhan” yang berkuasa dalam diri manusia. akan tetapi, ironisnya, karena tiap-tiap tuhan ingin disembah dan dipentingkan lebih dari yang lain, maka konflik kepentingan antara “tuhan-tuhan” itu pun terjadi secara sangat sengit. Sedemikian rupa sehingga nasib manusia itu sendiri terlupakan.
Agak berbeda dengan ciri dominasi syahwat yang rakus dan posesif, dominasi amarah akan mengubah manusia menjadi binatang buas yang agresif, ofensif dan destruktif. Tidak peduli apakah objeknya itu lemah, sama kuat, atau lebih kuat darinya. Buat jiwa yang terkuasai oleh amarah, aktualisasi kebuasan, dendam kesumat, penyerangan, penjarahan, dan penganiayaan adalah tujuan utama. Memenuhi dunia dengan teror, ancaman, ketakutan, kekerasan, kekejaman, darah, dan penganiayaan adalah obsesi manusia macam ini.
Dominasi khayal terhadap jiwa akan mentransformasi manusia menjadi homo ludens, pelamun, pendusta, penipu, penyihir dan sebagainya. Menurut para sufi, daya khayal yang mampu menampilkan sesuatu yang tidak ada dan tidak nyata menjadi seolah-olah ada dan nyata merupakan persinggahan favorit setan di dalam jiwa. Kekuatan khayal, imajinasi dan fantasi akan bekerja untuk memenuhi dunia dengan dusta, kepalsuan, tipu daya, dan angan-angan. Beribu ketidakmungkinan akan dibungkusnya dalam realitas-realitas semu.
Sebagai tempat bersemayamnya setan, para sufi menganjurkan agar kita pertama-tama memperkuat genggaman kita pada daya khayal. Khayalan yang terbang tinggi tak terkendali akan membuat setan nyaman dan aman merasuki jiwa, dan membisikkan keraguan, tipuan dan rayuan ke dalamnya. Daya khayal selanjutnya akan menghadirkan sebentuk jiwa palsu atau al-nasf al-khayaliyyah. Dengan jiwa palsu inilah khayal akan bekerja sama dengan syahwat dan amarah menundukkan kekuatan akal. Kemampuan akal memberi pertimbangan, mencapai kebenaran dan menemukan Tuhan akan dipaksa untuk mengaburkan kebenaran, menyemai keraguan, dan menyembah “tuhan-tuhan” palsu yang tak lain adalah ciptaan bersama syahwat-amarah-khayal tersebut.
Sebaliknya dari semua itu, bila akal berhasil memenangkan pertarungan ini, maka jiwa manusia akan bercahayakan keyakinan dan berhiaskan kemuliaan. Kerajaan jiwa akan berubah menjadi kerajaan Tuhan, taman impian para pecinta keindahan. Bergandengan dengan kehendak yang kuat, akal akan bisa memerintahkan semua potensi untuk sepenuhnya menyembah dan mengabdi kepada Pemilik dan Pemelihara sekalian alam.[2] (MK)
Bersambung…
Sebelumnya:
Catatan kaki:
[1] Lihat, Al-Qusyairi, The Principles of Sufism, Mizan Press, Berkeley, 1990, hal. 175.
[2] Lihat, Ruhullah Khomeini, Al-Arba’un Haditsan, Dar Al-Kitab Al-Islami, Qum, t.t., hal. 21-35.